Namaku
Ali Sumadinata. Nama depanku sama dengan nama dua kakekku dari pihak ibu dan
bapakku: Ali. Jika misalnya aku ditanya: Apakah kau bahagia? Kujawab: Ya, tentu
saja! Karena bagiku kebahagiaan tak semata ketika seseorang selalu hidup dalam
kesenangan. Sebaliknya, keberhasilan seseorang untuk bangkit dari kesulitan dan
kesempitan dan berjuang dalam kesukaran hidup itulah yang membuatnya bahagia.
Apa yang kusebut karena ia telah berhasil dan sanggup melakukan tindakan
bermakna yang membuatnya merasa menjadi manusia yang bebas dan merdeka.
Sempat
terpikir juga olehku mungkin saja orang-orang yang selama ini menjalani
kehidupan bersahaja sebagai para petani lebih merasakan kebahagiaan dalam hidup
mereka ketimbang orang-orang kota yang dalam keseharian mereka diatur oleh
jadwal, sehingga mereka seperti mesin yang tak bebas: menjadi manusia
birokratis yang gerak tubuh, hati dan pikirannya dikendalikan oleh aturan dan
jadwal. Hidup dalam mekanisme masyarakat budak yang telah menjadi bagian-bagian
dari mesin itu sendiri.
Orang-orang
bersahaja seperti para petani itu menurutku lebih terlihat tulus ketika mereka
bekerja di sawah-sawah. Sikap dan tindakan orang-orang desa juga lebih
menunjukkan solidaritas ketimbang orang-orang kota yang sangat individualis,
justru karena rasionalisme instrumental atau rasionalitas pragmatis mereka yang
mereka dapatkan dari pendidikan dan kehidupan modern mereka.
Barangkali,
kebahagiaan yang kupahami itu mendapatkan pembelaannya ketika membaca satu di
antara puisi-puisinya Rabindranath Tagore:
“Kau
kira aku anak kecil, Ibu, tapi kau keliru, sebab aku adalah Noto, tukang batu,
dan aku berusia tiga puluh tahun.
Tiap
pagi kunaiki kereta dan pergi ke kota dan kususun batu demi batu dengan semen
dan kapur dan kugambar dinding layaknya gambar menangkapku.
Kau
kira aku bermain rumah-rumahan dengan kerikil dan batu-batu, tetapi kukatakan
padamu aku membangun rumah sungguh-sungguh.
Ini
bukanlah rumah-rumah kecil sebab kudirikan tiga tingkat dan tiang-tiang yang
kuat.
Tetapi
bila kau tanyakan padaku kenapa aku berhenti di sana dan kenapa aku tak
meneruskan membangun tingkat demi tingkat hingga atapnya mencapai
bintang-bintang, kuyakin aku tak dapat mengatakannya padamu dan kuherani diriku
sendiri kenapa aku berhenti di mana saja pada segala.
Kunaiki
perancah saatku suka dan ini adalah kegembiraan yang lebih besar ketimbang
sekedar bermain-main. Kudengar pekerja-pekerja lelaki dan perempuan
bernyanyi-nyanyi dalam bekerja dan meratakan atap, gerobak-gerobak
berderak-derak sepanjang jalan-jalan, dan musik jalan dari pedagang-pedagang
dan para penjual barang logam dan buah-buahan; pada petang hari bocah-bocah
lari pulang dari sekolah dan gagak-gagak terbang berkoak-koak ke sarang mereka.
Kau
tahu, Ibu, aku tinggal di dusun kecil di tepi telaga.
Tetapi
bila kau tanyakan padaku mengapa kutinggal dalam sebuah gubuk beratap jerami
meski kubisa mendirikan rumah-rumah besar dari batu dan mengapa rumahku tidak
akan yang terbesar dari semuanya, kuyakin aku tiada dapat mengatakan padamu…”
Ibuku
sendiri seorang perempuan yang dicintai oleh orang-orang di kampungku, terutama
oleh kaum perempuan. Dan setelah ia wafat di tahun 2011 silam, penghormatan
orang-orang kampung, kaum perempuan yang mengenal ibuku itu beralih kepadaku.
Barangkali karena mereka tahu bahwa yang seringkali bersamanya saat ibuku
bekerja di sawah-sawah mereka adalah aku.
Ia
adalah tipe perempuan yang hanya akan keluar rumah jika ada keperluan penting
saja atau jika hendak membeli kebutuhan dapur dan untuk mendapatkan bahan
pelengkap makanan untuk makan kami. Ia sempat mengajar ngaji beberapa tahun
sebelum akhirnya berhenti karena alasan harus mengoptimalkan keluarga dan harus
istirahat sebab telah banyak bekerja, seperti menganyam daun-daun pandan atau
mengurus tanaman yang ditanamnya.
Di
masa-masa sulit, ibu-ibu atau perempuan-perempuan di kampung akan bertanya
kepada ibuku apakah kami punya beras untuk kebutuhan keluarga, dan karena
itulah aku seringkali membawakan gabah-gabah mereka ke tempat penggilingan,
yang berkat kerjaku membawa gabah mereka dengan menggunakan sepeda itu (di mana
sekarung gabah yang kubawa itu ditaruh di bagian tengah badan sepeda) kami
mendapatkan beberapa liter beras sebagai upah.
Di
masa-masa panen, ibu-ibu dan kaum perempuan di kampungku juga akan mengajak
kami untuk turut memanen padi di sawah-sawah mereka, dan aku pula yang selalu
ikut dengan ibuku. Dari pekerjaan itulah kami mendapatkan beberapa karung gabah
(mendapatkan 1/4 bagian), sesuai dengan kemampuan kami memanen padi di
sawah-sawah mereka, sebagai bagi hasil dari kerja kami membantu memanen padi
mereka. Begitulah cara orang-orang di kampung menolong kami. Itu adalah
masa-masa ketika adik-adikku belum lahir.
Sementara
itu, di masa-masa senggang dari musim panen padi hingga waktunya menanam padi
kembali, ibuku akan menanam kacang, kacang panjang, kangkung, dan juga Rosella,
yang kemudian akan ia jual kepada orang-orang kampung, dan tak jarang-orang di
kampungku dan orang-orang di kampung tetangga datang langsung kepada kami untuk
membeli bahan-bahan pangan yang ditanam dan dirawat ibuku.
Dari
penjualan kacang, kacang panjang, kangkung, dan Rosella (yang diolah menjadi
kopi oleh ibuku dan kami itu)-lah, kami mendapatkan uang untuk membiayai
sekolahku dan sekolah kakak perempuanku. Jika aku lebih dekat dan lebih
menghormati ibuku, tentu karena bagiku ibuku lah yang dapat kukatakan sebagai
orang yang setia dan punya komitmen, ketimbang bapakku.
Selain
menanam sejumlah sayuran dan yang lainnya, ibuku juga berusaha beternak,
seperti memelihara ayam dan unggas, yang ketika besar dapat dijual kepada
orang-orang yang lewat yang hendak ke pasar atau sepulang mereka dari pasar.
Ternak-ternak kami itu terutama sekali akan banyak yang membelinya di hari-hari
besar keagamaan, atau bila orang-orang di kampung hendak melaksanakan pesta pernikahan
anak mereka atau mengkhitankan anak mereka.
Dan
aku pula yang seringkali membantu ibuku untuk menangkap ayam-ayam itu bila
mereka kebetulan sedang dikeluarkan dari kandang saat ada orang yang hendak
membelinya tanpa diduga. Begitulah masa kanak dan masa remajaku yang lebih
banyak dihabiskan dengan ibuku –selain ibuku juga-lah orang pertama yang
mengajariku membaca dan mengaji Al-Quran di saat aku masih kanak-kanak.
Aku
pun masih ingat, suatu ketika, di tengah perjalanan pulang sekolah, hujan lebat
tiba-tiba turun bersama hembusan anginnya yang segera memintal dingin, dan aku
berteduh di bawah naungan ranting-ranting, dahan-dahan, dan daun-daun sepohon
rindang di tepi jalan, sebuah jalan yang bergandengan dengan sungai. Sebuah
sungai yang mengairi sawah-sawah kami, orang-orang desa.
Memang,
selama separuh perjalananku pulang sekolah itu, langit tampak mendung, dan
kupikir hujan baru akan turun sesampainya aku di rumah, sebuah praduga dan perkiraan
sepihak yang sungguh keliru dan kusesali. Maklum, kala itu akau ingin segera
pulang ke rumah, entah karena alasan apa. Malangnya aku. Hujan itu ternyata
berlangsung cukup lama, sekira setengah jam. Dan saat itulah aku dirundung
kesepian dan ketakutan seorang lelaki remaja.
Tak
ada kendaraan atau orang yang melintas selama hujan lebat itu turun dan
tercurah cukup deras dan riuh dengan anginnya yang segera menambah rasa dingin
tubuhku yang basah dan menggigil, sehingga gigiku bergemeretak. Saat itulah aku
serasa tengah berada di dalam dunia yang sangat sunyi. Barangkali pada saat itu
pula hatiku berdo’a.
Barangkali
pada saat itu pula aku sadar, meski masih seorang lelaki remaja, bahwa manusia
ternyata harus bersabar dan berdo’a ketika kejadian dan peristiwa yang tak
menyenangkan menimpanya. Bahkan, dan tentu saja ini pandangan moralisku setelah
menjadi lelaki dewasa, kebahagiaan yang kita alami dan kita rasakan akan lebih
bermakna setelah kita mengalami dan merasakan penderitaan.
Setelah
hujan lebat itu reda, aku menggerakkan dan melangkahkan kedua kakiku dalam
keadaan tubuh menggigil kedinginan, dan gigi-gigiku sesekali masih
bergemeretak. Untungnya kala itu, ada mobil truck pengangkut pasir melintas,
dan aku dibolehkan duduk menumpang di kursi sopir dan temannya, dan itulah
berkah yang tak kuduga pula. Betapa senangnya aku ketika aku dibolehkan
menumpang, karena tentu saja aku akan merasa lelah sekali jika harus berjalan
kaki dalam keadaan tubuh basah kuyup dan dihantam dingin yang membuat tubuhku
menggigil dan gigi-gigiku bergemeretak.
Sesampainya
di rumah, aku segera melepaskan baju seragam sekolahku dan langsung kuserahkan
kepada ibuku, dan ibuku menjemur baju seragam sekolahku itu di dapur, di
sebatang bambu yang melintang di atas dapur agar cepat kering dengan bantuan
suhu dapur bila ibuku memasak dengan menggunakan kayu bakar di tungku-tungku
dapur, karena keesokan harinya aku harus mengenakan baju seragam sekolahku
tersebut.
Ketika
itu rumah kami yang sederhana hanya berlantai tanah, tanpa semen atau keramik
seperti saat ini (seperti saat aku menulis catatan ini). Di lantai tanah itulah
kami akan menggelar tikar pandan yang dibuat oleh ibuku bila kami akan tidur,
atau untuk keperluan-keperluan lainnya seperti ketika makan dan menyambut
tamu-tamu yang datang ke rumah.
Sementara
itu, kebutuhan makan kami sehari-hari telah disediakan oleh apa saja yang kami
tanam, seperti sayur-sayuran yang kami tanam, semisal bayam, kangkung, kacang,
tomat, cabe rawit, dan lain sebagainya, di mana ibuku seringkali membuat menu
makanan seperti sambal dari cabe rawit, tomat, garam yang dibeli dari warung,
dan kulit buah Rosella berwarna merah yang ditanam ibuku, sehingga dengan kulit
Rosella itulah sambal yang dibuat ibuku lebih banyak dibanding bila tidak
ditambah dengan kulit merah buah Rosella.
Dalam
setiap waktu makan, ibuku akan selalu membuat atau memasak sayur dari bayam
atau kangkung yang dicampur bawang yang ditanam sendiri dan garam yang dibeli
dari warung. Kalau pun sesekali kami makan lauk, paling-paling ikan asin, tahu,
dan tempe yang dibeli dari pedagang keliling yang menggunakan sepeda.
Keberuntungan
lainnya, sesampainya di rumah setelah diguyur hujan lebat itu, adalah ketika
buku-buku catatan sekolahku tidak ikut basah karena kubawa dan kubungkus dengan
kantong plastik. Ide untuk menggunakan kantong plastik yang agak tebal dan
cukup besar untuk buku-buku itu berasal dari ibuku, dan terbukti lebih hebat
dibandingkan teman-temanku yang menggunakan tas yang tembus air, hingga
buku-buku mereka basah bila mereka kehujanan.
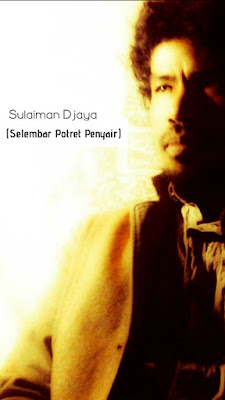
Tidak ada komentar:
Posting Komentar