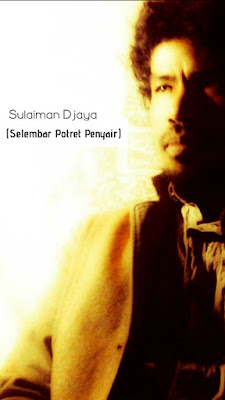Masa
kanak-kanak dan masa remaja barangkali adalah masa-masa keluguan dan kesahajaan
lelaki. Atau bahkan kenakalannya. Kupandangi lampu-lampu sebuah pabrik kertas,
yang karena tampak berkerlap-kerlip dan berkerumun, lebih mirip sebuah kota
kecil yang tak pernah tertidur. Dan memang sudah hampir tengah malam ketika
pintu ruang bacaku masih terbuka. Juga, meski cukup jauh, suara-suara mesin
pabrik kertas itu seolah datang dari setapak pematang di belakang rumah.
Tak
terasa, aku sudah bertahun-tahun hidup di dunia yang tak lagi sama seperti
ketika aku masih kanak-kanak dan remaja. Memang, sesuatu acapkali telah berubah
secara pelan-pelan ketika kita tak sedang memikirkannya, lagi-lagi ini
pandangan moralisku ketika kini menjadi lelaki dewasa, atau ketika kita, entah
sengaja atau tidak sengaja, tak menyadarinya.
Sementara,
malam tetap lengang seperti biasanya, tak ada bising atau keriuhan selain
suara-suara katak dan serangga. Namun, yang penting untuk diketahui, ketika aku
masih kanak-kanak, tempat yang kini menjadi kawasan pabrik kertas itu adalah
sejumlah rawa-rawa dan hutan belukar yang menjadi rumah bagi berbagai jenis
ular dan binatang-binatang lainnya.
Di
tempat itu pula, dulu sering kulihat gerombolan-gerombolan bermacam-macam
burung dan unggas yang singgah atau kembali terbang, dan sebuah kisah tentang
perempuan yang malang, yang kisahnya mirip film-film drama yang mengisahkan
sebuah kisah dari masa silam yang meski tak terlampau silam, tapi menyimpan
sejumlah peristiwa aneh.
Aku
baru terbangun dari tidur sebelum aku membuka pintu dan memandangi lampu-lampu
pabrik kertas itu, dan karenanya aku sengaja menahan dingin angin selepas
hujan. Sedangkan di antara atau di sekitar lintasan-lintasan pematang dan
hamparan sawah-sawah, gelap terasa kental dengan kebisuannya yang menyerupai
kiasan maut yang tengah terlelap karena cuaca lembab.
Ingatanku
tentang masa silam, muncul begitu saja ketika kupandangi barisan angka-angka
pada kalender yang terpampang dan berdiri di atas meja bacaku, di antara
beberapa buku, jurnal dan majalah yang terhampar dengan tenang, juga seperti
kematian dan masa silam. Masa-masa yang bagiku seperti lorong-lorong keheningan
yang panjang.
Tetapi
kini, sungai telah memiliki dinding-dinding batu dan pohon-pohon rindang
sepanjang jalan telah digantikan barisan tiang-tiang beton, bersamaan dengan
hadirnya pabrik kertas dengan dua cerobong asap raksasanya yang mengepulkan
asap ke udara.
Namun,
meski bagaimana pun, sebelum pabrik kertas itu dapat hadir dengan megah seperti
sekarang ini, ada sebuah cerita tentang Nyi Randa, seperti yang telah
kukatakan, yang kemudian menjadi nama tempat yang kini telah digantikan pabrik
kertas itu, yaitu Tegal Nyi Randa.
Ketika
pabrik kertas mulai dibangun di tegal itu, orang-orang bercerita tentang
sepohon besar yang berdiri kokoh kembali keesokan harinya setelah dirobohkan.
Pohon besar itulah yang oleh orang-orang dipercaya sebagai jelmaan Nyi Randa
bertahun-tahun kemudian setelah ia melarikan diri ke rawa-rawa dan gugusan
hutan belukar ketika seorang jawara membunuh suaminya tak lama setelah
dilangsungkan resepsi pernikahan Nyi Randa dan suaminya yang terbunuh itu.
Sebab, setelah kejadian itu, seperti cerita orang-orang di sekitar sungai
Ciujung, Nyi Randa tak lagi ditemukan.
Mendapati
pohon besar yang telah dirobohkan dengan menggunakan alat berat itu berdiri
kokoh kembali keesokan harinya, pihak perusahaan pun merobohkan lagi pohon
besar itu. Tetapi hasilnya tetap sama, pohon besar itu kembali berdiri seperti
semula.
Kejadian
itu pun segera menyebar luas di masyarakat, dan memunculkan dua pendapat: pihak
perusahaan tetap ngotot untuk melenyapkan pohon tersebut, sementara sebagian
masyarakat menginginkan agar pohon besar tetap ada di tempatnya seperti telah
bertahun-tahun ada. Butuh waktu berhari-hari bagi pihak perusahaan untuk
mewujudkan keinginan mereka sebelum akhirnya mereka berhasil membayar para
dukun dan beberapa orang untuk melenyapkan pohon besar tersebut dengan bayaran
yang cukup besar bagi orang-orang yang tak memiliki pekerjaan resmi.
Hanya
saja ceritanya tak cuma sampai di situ. Beberapa hari setelah pohon besar itu
berhasil dilenyapkan, pihak perusahaan dikagetkan dengan banyaknya kehadiran
ular-ular yang datang tiba-tiba entah dari mana ke setiap sudut dan tempat di
kawasan pabrik kertas yang sedang dibangun itu, hingga beberapa pekerja pun
meninggal karena serangan ular-ular tersebut. Sementara, di waktu malam, para
pekerja seolah selalu mendengar suara seorang perempuan tengah bersenandung dan
beberapa pekerja terjatuh dari konstruksi bangunan karena efek teror nyanyian
gaib tersebut.
Dan
seperti pada kejadian-kejadian sebelumnya, orang-orang pun mempercayai bahwa
perempuan yang selalu bersenandung di waktu malam itu adalah Nyi Randa yang
tengah merana dan merasakan kesepian karena telah terusir untuk kedua kalinya.
Aku jadi teringat kembali tentang kisah Nyi Randa itu ketika kupandangi
lampu-lampu pabrik kertas, yang dulunya adalah rawa-rawa dan habitat para
unggas, burung-burung, dan binatang-binatang Tuhan lainnya.
Sejumlah
burung-burung dan para unggas, yang ketika terbang melintasi cakrawala pagi
atau senja, membuatku membayangkan diri ingin seperti mereka yang dapat pergi
dan terbang kapan saja.
Mungkin
seperti itu pula riwayatku sendiri. Selain terserak dalam ingatan dan kenangan
yang tak lagi utuh, riwayat usiaku juga terekam dalam foto-foto, dan sama-sama
tak lebih sejumlah fragmen sebagaimana ingatan dan kenangan yang hanya dapat
kuangankan. Sebuah foto yang kupandangi seakan mengajakku kembali untuk
menyusuri jejalan setapak sungai di bawah barisan pohon-pohon rindang yang
mirip sebuah terowongan kota-kota metropolitan sekarang ini. Jejalan setapak
sepanjang sungai yang sebenarnya hanya bisa kukhayalkan. Dan diriku yang
kuingat-ingat itu pun sebenarnya tak lebih orang lain yang telah tak ada. Sedangkan
dorongan khayalan itu sendiri adalah perasaan cacat dan tak lengkap dalam
diriku sebagai lelaki: Ali Sumadinata, atau mungkin dalam diri Anda. Itulah
yang lazim disebut sebagai ironi dan dilema Narcissus: “permainan kehilangan
dan menemukan”.
Dari
segi budaya massa, tahun 70-an bisa dibilang sebagai eranya The Beatles dan
Rock N Roll, ketika generasi muda mengenakan busana yang lebar di ujung kakinya
dan ketat di bagian paha mereka. Sebuah masa yang bukan milikku, dan karena itu
tak banyak yang bisa kuketahui di tahun-tahun 70-an, selain mereka-reka, dan
itulah yang kulakukan, ketika membuka album foto-foto keluarga, yang sebagian
besar sudah kusam dan sudah tak lagi mencerminkan jepretan pertama. Namun di
dalam hati, diam-diam aku merasa kagum dan berterimakasih kepada fotografi,
yang meski aku lahir di pedesaan, keluargaku bisa dikatakan sadar dokumentasi.
Dalam
keadaan seperti itu, aku hanya bisa tersenyum-senyum sendiri di ruangan
tempatku menulis dan membaca ketika memandangi foto-foto keluarga dan membaca
majalah-majalah di tahun-tahun 70-an dan 80-an yang kudapatkan dari paman dan
sepupuku dari pihak almarhumah ibuku.
Dalam
foto-foto itu, aku adalah antara lain seorang bocah yang baru bisa merangkak
dan seorang siswa kelas satu sekolah dasar dengan kondisi punggung yang masih
tegak, tidak seperti sekarang ini yang mudah lelah dan merasa sakit bila tidak
bersandar. Bersamaan dengan itu, aku tiba-tiba tergoda untuk membayangkan dan
mengingat-ingat malam-malam di desa di tahun-tahun 80-an yang masih menggunakan
lampu-lampu minyak. Aku tergoda untuk kembali membayangkan dan mengingat-ingat
keheningan malam yang begitu panjang, sepanjang jalan dan sungai, sepanjang
pohon-pohon rimbun nan rindang, di mana suara-suara serangga dalam kegelapan
selepas hujan semakin menambah keheningan.
Rasa
ingin membayangkan kembali masa silam itu justru tersulut di saat-saat aku
memandangi foto-foto yang tersimpan di album keluarga, di saat-saat aku membaca
majalah-majalah era 70-an dan 80-an, yang di saat tidak menceritakan semuanya,
tapi pada saat yang sama menyimpan banyak hal, yaitu ingatan dan kenangan.
Kemudian
aku seolah mendapatkan suatu kesan bahwa sebuah gambar, ternyata, sama-sama
bisa bercerita banyak hal sebagaimana satu buku sejarah, atau bahkan bisa lebih
banyak bercerita ketimbang satu buku sejarah, justru karena ia rentan dan
selalu memiliki kemungkinan untuk ditafsirkan. Seperti halnya sebuah komposisi
musik yang ingin selalu Anda dengarkan, karena ada sesuatu yang ingin Anda
ceritakan dengannya, meski untuk Anda sendiri. Dan sebuah foto bercerita banyak
kepada Anda sekaligus tetap menyimpan dan menyembunyikan yang lainnya, seperti
juga bagiku.
Seperti
itulah, sebuah foto yang kupandangi sanggup membuatku tergoda untuk
mengingat-ingat sejumlah kenangan yang menyenangkan dan yang menyedihkan.
Memancing rasa sentimentilku untuk membayangkan masa silam yang telah tak ada.
Rasa sentimentil yang tersulut begitu saja ketika aku merasa bosan atau jenuh
dengan apa yang tengah kulakukan dalam kesendirian.
Mungkin,
pada saat-saat itu, Anda tak perlu membaca kembali catatan harian Anda, itu pun
bila Anda punya catatan harian. Atau ketika Anda ingin merenungi sejenak
perjalanan hidup Anda, mungkin cukup memandangi foto-foto dalam album fotografi
milik Anda.
Sementara
bagiku sendiri, ketika memandangi foto-foto di album keluarga, seperti yang
telah kukatakan itu, aku tiba-tiba membayangkan kembali masa-masa ketika malam
terasa begitu panjang dan hujan membuat keheningan terasa semakin kental di
pedesaan, di saat aku hanya bertemankan selampu minyak di meja belajar.
Katakanlah, sebuah foto atau sebuah gambar bisu tentang diri Anda, justru yang
seakan-akan sanggup menghentikan dan menyandra masa lalu untuk siap
menghadirkannya kembali ke masa sekarang di mana Anda hidup dan memandanginya.
Pada
kasus tersebut, sebuah foto menjadi intim dan berarti bukan karena sebuah foto
baru jadi atau baru dicetak, tetapi karena ia sudah tersimpan lama dan
sekaligus telah menyimpan tahun-tahun yang pernah Anda jalani dalam hidup,
tahun-tahun yang dalam keadaan tertentu dalam hidup Anda mungkin terasa belum
jauh dan serasa baru beberapa waktu saja. Dan utamanya untuk kasusku sendiri,
foto-foto di album keluarga itu tak menerakan tanggal dan tahun kapan foto itu
diambil dan dibuat oleh si juru fotoya, hingga aku mesti mereka-reka sendiri
tentang masa dan waktu pembuatan dan pencetakannya.
Karena
itu, bila aku boleh menyimpulkan, sebuah foto bisa mengatakan sesuatu yang tak
bisa dilakukan atau diceritakan oleh lembar-lembar halaman catatan harian.
Contohnya adalah wajah-wajah yang sedih atau riang dalam sebuah foto atau
gambar, tetap saja memancarkan keunikannya sendiri yang berbeda-beda pada
setiap orang atau wajah, pada setiap moment atau kondisi-kondisi tertentu.
Bersama
sebuah foto, ingatan yang memang sebenarnya hanya angan-angan kita, diberi
kesempatan untuk memuaskan apa yang ingin direka dan digambarnya kembali. Meski
pada saat yang sama ia hanya bisa mengembarai kegelapan dan
khayalan-khayalannya sendiri. Tetapi, mungkin karena hal itu pula, rasa senang
senantiasa direkonstruksi, di saat Anda ingin mengingat-ingat kembali kejadian
dan peristiwa yang pernah ada atau yang melatarbelakangi keberadaan foto itu
sendiri, di saat foto itu sendiri sebenarnya sudah terbebas dari peristiwa atau
kejadian yang pernah Anda alami atau yang pernah Anda rasakan.
Persis
seperti itulah, dengan dan bersama sebuah foto, apa yang kulakukan adalah
mengarang kembali sejarah dan perjalanan hidupku. Anggaplah sebuah foto tak
ubahnya satu puisi singkat yang bisa menceritakan banyak hal sekaligus
menyamarkannya pada saat bersamaan. Fungsi figuratifnya telah membuatnya
menjadi kecil sekaligus longgar dan terbuka untuk selalu ditafsirkan.
Namun,
di atas semua yang telah kukatakan itu, ada juga mungkin sesuatu yang lain.
Sebutlah ketika Anda memandangi foto diri Anda, terutama diri Anda di suatu
masa yang telah berlalu bertahun-tahun, ada sesekali perasaan bahwa Anda tengah
memandangi orang lain, disadari atau tidak disadari. Dan pada saat itu pula,
Anda pun tengah mengagumi diri Anda yang lain, seperti ketika Anda memandangi
diri Anda di cermin, di mana sebuah cermin berfungsi sebagai pemantul sekaligus
pemisah (pemecah) diri Anda. Hanya saja sebuah foto diri Anda di masa silam
mengajak untuk kembali menemukan diri Anda, dan itulah yang bisa kita sebut
sebagai ingatan yang disandera sekaligus diceritakan oleh sebuah foto yang
telah lama tersimpan.
Ingatan
dan sebuah foto paling pribadi milik Anda, sebagaimana sebuah puisi romantis
yang bukan lagi milik penyairnya, telah memiliki kehidupannya sendiri,
kehidupan yang telah berpisah sekaligus masih dibagi dengan diri Anda, atau
katakanlah, merebut figur Anda demi keberadaan dirinya sendiri. Karena itu,
yang Anda lakukan tak lebih mengarang kembali ketika Anda ingin memasuki
ingatan, atau ketika Anda mengingat-ingat kejadian yang telah berlalu
bertahun-tahun. Meski pada kadar yang paling sentimentil, Anda merasa
seakan-akan waktu tak beranjak, apa yang lazim disebut sebagai daya-tarik
kesedihan dan keriangan sesaat.
Hingga
bisa dikatakan, sebuah foto, sebagaimana sebuah cermin, menjadi ada karena
bukan hanya mampu menampilkan citra Anda, tetapi lebih dari itu, ia mampu
menunjukkan dan menghadirkan “orang lain”, orang lain yang anehnya
terus-menerus Anda identifikasi sebagai diri Anda. Dalam kajian historiografi,
contohnya, sebuah foto telah mampu menghadirkan kembali kejadian-kejadian atau
pun peristiwa-peristiwa di masa lalu yang sebenarnya sudah tidak ada.
Sementara
itu, bagiku sendiri, sebuah foto yang kupandangi seakan mengajakku kembali
untuk menyusuri jejalan setapak sungai di bawah barisan pohon-pohon rindang
yang mirip sebuah terowongan kota-kota metropolitan sekarang ini. Jejalan
setapak sepanjang sungai yang sebenarnya hanya bisa kukhayalkan. Dan diriku
yang kuingat-ingat itu pun sebenarnya tak lebih orang lain yang telah tak ada.
Sedangkan dorongan khayalan itu sendiri adalah perasaan cacat dan tak lengkap
dalam diriku sendiri, atau mungkin dalam diri Anda. Itulah yang lazim disebut
sebagai ironi dan dilema Narcissus: “permainan kehilangan dan menemukan”.
Pada
konteks seperti itu, nilai makna dan arti sebuah foto terletak pada
kemampuannya untuk membangkitkan sentimentalitas personal. Ketika detil dan
ketaklengkapan telah membebaskan dirinya untuk ditafsirkan olehku atau oleh
Anda. Ketika ia membiarkan dirinya untuk terus direkonstruksi sejauh menyangkut
kejadian dan latarbelakang yang menyediakan peluang bagi ingatan untuk
melakukan tugasnya dalam pengembaraan-pengembaraan permainan kehilangan dan
menemukan.
Kita
juga sebenarnya sudah begitu tahu, dari sudut historiografis, fotografi telah
menjalankan fungsi artifak dan hiorieglif, situs dan prasasti, meski yang
diceritakan kepada kita lebih merupakan pecahan, potongan, dan kepingan
kejadian, yang dari itu, kita sendiri yang mesti merangkai keutuhan dan
kelengkapannya. Di sini dikatakan, misalnya, detil-detil sebuah foto akan mampu
memberikan materi untuk upaya rekonstruksi kejadian dan pemahaman peristiwa,
meski sebenarnya tak pernah berhasil menemukan keutuhan.
Sebagai
contoh lainnya misalnya dikatakan, dari kualitas warna dan cahaya, kita bisa
mereka-reka apakah sebuah foto yang kita pandangi dibuat dan diambil pada waktu
pagihari, sianghari, sorehari, ataukah malamhari. Sementara itu, detil-detil
material dan situasi sebuah tempat yang tersimpan dan tertangkap sebuah foto
akan juga mengatakan kepada kita tentang situasi sebuah jaman, trend yang sedang
berlaku, atau juga situasi sosial-budaya yang bisa dicontohkan dengan materi
dan situasi busana, arsitektur tempat, produk-produk industri-ekonomi, dan lain
sebagainya. Sesuatu yang dulu orang-orang purba gambarkan kepada kita melalui
ukiran, lukisan, simbol-simbol, dan rumus-rumus seperti yang dicontohkan dengan
baik oleh hieroglif orang-orang Mesir purba, yang adalah juga para seniman
grafis yang cakap secara matematis dan estetis.
Tetapi,
karena ketaklengkapannya itu, dan ini pun diakui oleh para arkeolog dan
sejarawan, sebuah prasasti, hieroglif, atau pun fotografi, hanya memberikan
kepingan cerita, bukan keseluruhan peristiwa atau pun kejadian historis yang
padu dan lengkap. Pada celah itulah dibutuhkan interpretasi alias penafsiran
dan angan-angan sang arkeolog atau pun sang sejarawan, atau apa yang aku
sendiri akan menyebutnya sebagai upaya “mengarang kembali” peristiwa dan
kejadian. Hingga karena demikian, historiografi sekalipun tak pernah terbebas
dari angan-angan, justru karena setiap fakta dan bukti historiografis pada
akhirnya mesti ditafsirkan, di saat yang hadir kepada kita hanya pecahan dan
kepingan, bukan peristiwa atau kejadian yang utuh. Ia ada sebagai sesuatu yang
cacat dan tak lengkap.
Tepat
pada saat itulah, Anda hanya berusaha mengangankan dan mengarang kembali
kejadian atau pun latarbelakang sebuah foto yang Anda pandangi atau yang tengah
Anda selidiki, di saat figur Anda yang ada dalam foto tersebut telah menjadi
orang lain yang milik masa lalu. Di saat milik Anda yang sesungguhnya hanyalah
angan-angan itu sendiri. Dan karena itu, semakin tak lengkap sebuah foto,
semakin kreatif pula angan-angan Anda untuk mengarang kembali sebuah peristiwa
atau kejadian yang dapat membuat sebuah foto berarti bagi Anda, di saat Anda
sendiri hanya bisa mengangankan kembali gambar-gambar buram ingatan. Seperti
itulah kisah hidupku yang kutulis dalam otbiografiku ini.
Dan
seperti itu pulalah historiografi, sebagaimana dipahami Homerus, Virgilius, dan
Plutarch, tak sekadar dokumentasi prosaik, tetapi sebuah deskripsi yang hidup,
yang karenanya Homerus dan Virgilius menuliskannya dalam bentuk teater puitis
melalui media puisi, di mana ingatan menjadi demikian hidup karena dituliskan
dan digambarkan secara teatrikal. Sebab itu tidak berlebihan, ketika Shakespeare
mengaku diri lebih banyak belajar tentang sejarah dari puisi-puisi dan
drama-drama Yunani, atau dari epik-epik lainnya. Dan aku pun telah banyak
menyalin fiksi riwayat hidupku menjadi fiksi yang lain.